Pendahuluan
Pendidikan tidak semata-mata tentang mentransfer pengetahuan atau keterampilan dari pendidik ke peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan menyangkut proses pemanusiaan manusia, menjadikan peserta didik sebagai subjek aktif dalam mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan. Dalam konteks ini, pendekatan humanisme dalam pendidikan menjadi sangat relevan. Humanisme menekankan pada penghargaan terhadap martabat, potensi, dan kebebasan individu dalam proses belajar. Artikel ini akan menelusuri bagaimana humanisme memandang manusia sebagai subjek pendidikan dan bagaimana pandangan ini berkontribusi pada praktik akademik di era modern.
1. Hakikat Manusia dalam Perspektif Humanisme
Humanisme, secara filosofis, berakar pada pandangan bahwa manusia memiliki potensi bawaan untuk berkembang dan mencapai kebaikan melalui akal dan pengalaman. Dalam konteks pendidikan, ini berarti setiap individu memiliki potensi unik yang harus dihargai dan dikembangkan secara holistik. Berbeda dari pendekatan mekanistik atau otoriter, humanisme melihat peserta didik bukan sebagai “gelas kosong” yang harus diisi, melainkan sebagai pribadi yang telah memiliki dasar untuk tumbuh melalui bimbingan yang tepat.
2. Sejarah Pemikiran Humanisme dalam Pendidikan
Pandangan humanisme dalam pendidikan memiliki akar yang panjang dalam sejarah filsafat.
- Plato percaya bahwa pendidikan adalah sarana untuk mengingat kembali pengetahuan yang sudah ada dalam jiwa. Meskipun cenderung idealis, pandangannya telah membuka diskusi tentang pentingnya jiwa dan nilai dalam proses belajar.
- Renaissance Humanists seperti Erasmus mengedepankan pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai moral dan literasi, sebagai upaya untuk membentuk manusia seutuhnya.
- Jean-Jacques Rousseau melalui karyanya Émile, menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat dan tahap perkembangan anak.
- John Dewey, salah satu tokoh penting dalam pendidikan progresif, mengajukan ide bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada pengalaman, partisipasi aktif, dan relevansi sosial.
- Paulo Freire, tokoh pendidikan kritis, berpendapat bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menindas. Dalam Pedagogy of the Oppressed, ia memperkenalkan konsep “pendidikan dialogis” yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang berpikir dan bertindak.
3. Konsep Subjek dalam Pendidikan
Dalam pendekatan humanistik, manusia sebagai subjek pendidikan berarti ia adalah pelaku aktif yang memiliki otonomi, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap proses belajarnya. Subjektivitas ini melibatkan:
- Kesadaran Diri: Peserta didik memiliki kapasitas untuk merefleksikan dirinya, tujuan hidup, dan proses belajar.
- Kebebasan Berpikir: Pendidikan memberikan ruang untuk berpikir kritis, bertanya, dan mempertanyakan kebenaran yang ada.
- Keterlibatan Emosional dan Sosial: Belajar tidak hanya proses kognitif, tetapi juga emosional dan sosial, di mana relasi dan konteks sangat mempengaruhi hasil.
4. Implikasi dalam Dunia Akademik
Humanisme memberikan dasar filosofis bagi berbagai praktik pendidikan modern:
- Student-Centered Learning: Pendekatan ini memberi ruang kepada peserta didik untuk memilih, mengeksplorasi, dan menentukan arah belajarnya.
- Pembelajaran Kolaboratif: Mendorong kerja sama antar individu, bukan kompetisi semata, sebagai bagian dari pengalaman belajar.
- Evaluasi Autentik: Penilaian dilakukan tidak hanya berdasarkan angka, tapi juga melalui proyek, refleksi diri, dan partisipasi aktif.
- Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan: Menghargai perbedaan dan kebutuhan individual peserta didik sebagai bagian dari pendekatan yang menghargai kemanusiaan.
5. Tantangan dan Realitas di Indonesia
Meskipun konsep humanisme sangat ideal, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan:
- Struktur Kurikulum yang Kaku: Kurikulum nasional yang padat dan terstandarisasi seringkali tidak memberi ruang bagi pendekatan humanistik.
- Tekanan Ujian dan Nilai: Sistem evaluasi berbasis angka masih mendominasi dan menggeser esensi pembelajaran yang mendalam.
- Keterbatasan Sumber Daya: Guru sering kali harus menangani banyak siswa dengan fasilitas yang terbatas, menyulitkan pendekatan personal dan reflektif.
- Ketimpangan Pendidikan: Masih banyak daerah di Indonesia yang belum mendapat akses pendidikan yang layak, menjauhkan mereka dari pendidikan yang memanusiakan.
6. Peran Guru dan Dosen dalam Menerapkan Humanisme
Para pendidik memiliki peran penting dalam menjadikan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Peran tersebut mencakup:
- Fasilitator dan Mitra Belajar: Guru bukan sumber kebenaran mutlak, melainkan pendamping dalam proses eksplorasi dan pembelajaran.
- Penggerak Dialog dan Refleksi: Mengajak peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan merefleksikan nilai-nilai kehidupan.
- Pemodel Nilai-Nilai Kemanusiaan: Menunjukkan empati, kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab dalam interaksi sehari-hari.
- Pencipta Lingkungan Belajar yang Aman dan Inklusif: Membentuk ruang kelas yang memberi kebebasan berekspresi dan menghargai perbedaan.
7. Pendidikan Humanistik di Era Digital
Perkembangan teknologi membawa tantangan dan peluang dalam menerapkan pendidikan humanistik:
- Tantangan: Teknologi dapat mengarah pada individualisme, ketergantungan, dan mengurangi interaksi antar manusia secara langsung.
- Peluang: Teknologi juga bisa memperluas akses informasi, memperkaya pengalaman belajar, dan mendukung personalisasi pembelajaran.
Dalam konteks ini, penting bagi pendidik untuk tetap menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penggunaan teknologi, agar pembelajaran tidak kehilangan arah etik dan sosialnya.
Kesimpulan
Pendidikan yang memanusiakan adalah pendidikan yang melihat manusia bukan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki potensi, kesadaran, dan kebebasan. Pandangan humanisme dalam dunia akademik menawarkan paradigma yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan dengan menghargai individualitas, relasi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah berbagai tantangan pendidikan di Indonesia, semangat humanisme perlu terus dikembangkan dan diterapkan secara kontekstual dan kreatif, demi terwujudnya pendidikan yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa.











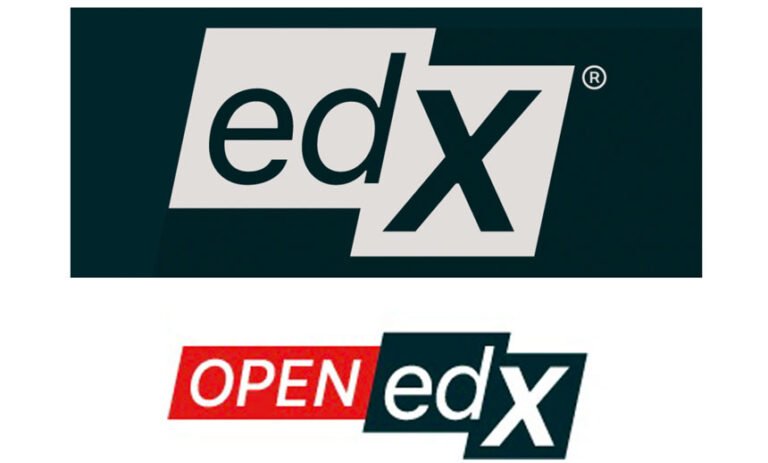




















Responses