Asap gas air mata yang membubung di depan gedung parlemen, barikade jalan yang terbakar, dan bentrokan antara massa dengan aparat menjadi pemandangan yang sayangnya cukup akrab dalam lanskap demokrasi Indonesia. Di satu sisi, demonstrasi adalah detak jantung demokrasi, sebuah kanal vital bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Namun di sisi lain, potret anarkisme yang terkadang menyertainya menimbulkan pertanyaan fundamental: di manakah sebenarnya batas antara hak protes yang konstitusional dan aksi anarkis yang merupakan tindak pidana?
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Setiap kali aksi massa besar terjadi, ruang publik terbelah antara dukungan terhadap substansi tuntutan dan kecemasan akan potensi kericuhan yang mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas. Artikel ini bertujuan untuk membedah secara mendalam dan objektif kerangka hukum yang mengatur demonstrasi di Indonesia. Dengan memahami aturan demo yang benar, baik masyarakat maupun aparat dapat menavigasi ruang demokrasi secara lebih bertanggung jawab, memastikan suara kritis tersampaikan tanpa harus mengorbankan keamanan dan supremasi hukum.
Landasan Hukum Hak Berpendapat di Indonesia
Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum bukanlah sebuah hadiah dari negara, melainkan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Landasan utamanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 28 UUD 1945 secara tegas menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Jaminan ini diperkuat lebih lanjut pasca-amandemen, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat adalah pilar fundamental negara hukum demokratis Indonesia. Hak ini juga selaras dengan instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Namun, penting untuk dipahami bahwa konstitusi dan peraturan turunannya menggarisbawahi sebuah konsep kunci: kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, pelaksanaan hak ini tidak absolut dan harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan memelihara keutuhan bangsa. Filosofi hukum di Indonesia tidak melihat kebebasan berekspresi dan ketertiban umum sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan sebagai dua nilai yang saling bergantung. Ruang demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika kebebasan diekspresikan dalam koridor hukum yang menjamin ketertiban bagi semua.
Panduan Praktis Aturan Demo Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998
Sebagai respons langsung terhadap tuntutan demokratisasi di era Reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini bukanlah alat untuk membungkam kritik, melainkan sebuah kerangka kerja (framework) untuk memastikan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Berikut adalah poin-poin krusial dari UU ini yang menjadi aturan demo baku di Indonesia.
Pemberitahuan, Bukan Perizinan
Ini adalah salah satu aspek yang paling sering disalahpahami. Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998 mewajibkan penyelenggara aksi untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Penting untuk dicatat, kata yang digunakan adalah “pemberitahuan”, bukan “izin”. Perbedaan ini sangat fundamental. “Izin” mengimplikasikan bahwa negara memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak hak dasar warga negara. Sebaliknya, “pemberitahuan” menegaskan bahwa hak untuk berdemonstrasi sudah melekat pada warga negara, dan pemberitahuan tersebut berfungsi sebagai mekanisme koordinasi agar aparat dapat menjalankan kewajibannya untuk memberikan pengamanan dan mengatur lalu lintas, bukan untuk menilai atau menyensor isi dari aspirasi yang akan disampaikan.
Hak dan Kewajiban yang Seimbang
UU ini mengatur secara jelas hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat.
- Hak Peserta Aksi: Warga negara berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum selama aksi berlangsung damai.
- Kewajiban Peserta Aksi: Di sisi lain, setiap peserta berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan bangsa.
- Kewajiban Aparat Pemerintah: Aparat berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, dan menyelenggarakan pengamanan untuk memastikan aksi berjalan lancar.
Batasan Ruang, Waktu, dan Atribut
Kebebasan yang bertanggung jawab juga diwujudkan melalui batasan yang jelas untuk mencegah gangguan terhadap fungsi-fungsi vital negara dan masyarakat.
- Lokasi Terlarang: Demonstrasi dilarang dilaksanakan di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan objek-objek vital nasional lainnya.
- Waktu Pelaksanaan: Aksi di tempat terbuka dibatasi dari pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat. Aturan ini dibuat untuk mempertimbangkan hak masyarakat lain untuk beristirahat dan menjaga keamanan pada malam hari.
- Atribut Terlarang: Pasal 9 ayat (3) secara eksplisit melarang peserta membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, seperti senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak.
Aparat dapat membubarkan sebuah demonstrasi jika melanggar ketentuan-ketentuan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998.
Ketika Demonstrasi Menjadi Tindakan Anarkis
Batas antara hak protes dan anarki menjadi sangat jelas ketika tindakan peserta melanggar hukum pidana. Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa pelaku atau peserta aksi yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pada titik ini, status hukum seorang individu berubah. Ia tidak lagi dilihat sebagai “demonstran” yang dilindungi haknya, melainkan sebagai “pelaku tindak pidana”. Penting untuk digarisbawahi bahwa pertanggungjawaban hukum bersifat individual. Tindakan anarkis oleh segelintir oknum tidak serta-merta menjadikan seluruh aksi tersebut ilegal, dan aparat memiliki kewajiban untuk menindak pelaku kriminal secara spesifik tanpa melakukan kekerasan terhadap massa yang masih bertindak damai.
Beberapa pasal KUHP yang paling relevan untuk menjerat pelaku anarkisme dalam demonstrasi antara lain:
- Pasal 170 KUHP: Tentang kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Ancaman hukumannya bisa mencapai 5 tahun 6 bulan penjara, dan bisa lebih berat jika mengakibatkan luka berat atau kematian.
- Pasal 406 KUHP: Tentang perusakan barang milik orang lain. Siapa pun yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak fasilitas umum seperti halte bus, rambu lalu lintas, atau kendaraan dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- Pasal 55 dan 56 KUHP: Tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pasal ini memungkinkan penegak hukum untuk menjerat tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, turut serta, atau sengaja memfasilitasi terjadinya kejahatan.
Menjaga Demokrasi adalah Tanggung Jawab Bersama
Batas antara hak protes yang sah dan aksi anarkis yang ilegal sesungguhnya tidak abu-abu. Batasan itu telah diatur dengan jelas dalam UU No. 9 Tahun 1998 sebagai koridor prosedural dan dalam KUHP sebagai garis merah pidana. Demonstrasi adalah hak, sedangkan perusakan, kekerasan, dan provokasi adalah kejahatan.
Menjaga agar demonstrasi tetap berada di jalur yang konstitusional adalah tanggung jawab bersama. Bagi penyelenggara dan peserta aksi, mematuhi aturan demo—mulai dari pemberitahuan, menjaga ketertiban, hingga tidak membawa benda berbahaya—bukanlah bentuk ketundukan, melainkan sebuah strategi cerdas untuk menjaga legitimasi moral dan hukum dari perjuangan mereka. Bagi aparat keamanan, pendekatan yang humanis, proporsional, dan memfasilitasi (bukan merepresi) adalah kunci untuk mencegah eskalasi dan memenuhi mandat undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia.
Pada akhirnya, demonstrasi yang tertib dan anarkisme yang merusak adalah dua hal yang berbeda. Memahami perbedaannya adalah langkah awal untuk merawat demokrasi Indonesia agar tetap sehat, kritis, dan beradab.











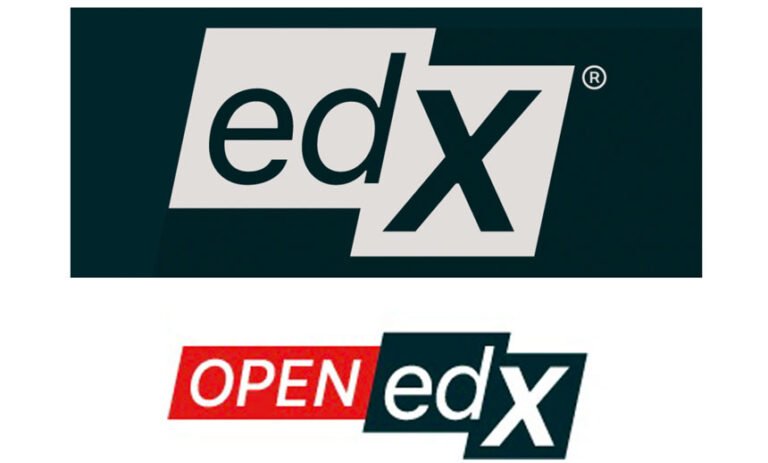




















Responses