Pendahuluan
Setiap bangsa memiliki tokoh penting yang membentuk arah dan wajah pendidikannya. Di Indonesia, nama Ki Hadjar Dewantara melekat erat dengan pendidikan nasional yang berpihak pada rakyat. Beliau bukan hanya pendiri Taman Siswa, tetapi juga seorang pemikir, pejuang kemerdekaan, dan pendidik visioner yang melahirkan prinsip-prinsip mendalam tentang proses belajar yang merdeka. Gagasan-gagasannya tidak hanya relevan pada masanya, tapi juga menjadi fondasi pendidikan modern Indonesia saat ini.
Lahir dari keluarga bangsawan Jawa dan memilih jalan hidup yang berpihak pada kaum tertindas, Ki Hadjar Dewantara mencerminkan semangat pengabdian sejati bagi bangsa. Artikel ini akan membahas perjalanan hidup, pemikiran, serta kontribusinya yang menjadikan beliau layak disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
1. Masa Muda dan Perjalanan Awal
Ki Hadjar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Sebagai bagian dari kerabat Keraton Yogyakarta, ia mendapat akses pendidikan yang cukup langka bagi kaum pribumi saat itu. Ia mengenyam pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School), kemudian melanjutkan ke STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen), sekolah kedokteran untuk pribumi. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan kedokterannya karena alasan kesehatan.
Kegemarannya dalam menulis dan berpikir kritis membawanya masuk ke dunia jurnalistik dan aktivisme. Ia bekerja sebagai wartawan di berbagai surat kabar seperti De Express, Oetoesan Hindia, dan Kaoem Moeda. Melalui tulisan-tulisannya, ia menyuarakan kritik tajam terhadap ketidakadilan sistem kolonial, terutama dalam bidang pendidikan dan perlakuan terhadap pribumi.
Salah satu tulisannya yang paling terkenal adalah “Als Ik Een Nederlander Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda), yang terbit tahun 1913. Tulisan ini mengkritik keras perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda di tanah jajahan. Akibat tulisan ini, ia bersama dua tokoh lainnya — Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo — diasingkan ke Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan Trio Tiga Serangkai.
2. Menyerap Ilmu di Belanda
Pembuangan ke Belanda justru menjadi momen penting bagi Ki Hadjar dalam memperdalam ilmu pendidikan. Ia memanfaatkan masa pengasingan dengan belajar tentang sistem pendidikan Eropa, khususnya pemikiran tokoh-tokoh seperti Froebel, Montessori, dan Tagore. Ia mulai melihat bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses pembentukan karakter dan kemerdekaan berpikir.
Selama di Eropa, ia juga menyadari betapa sistem pendidikan kolonial Indonesia dirancang untuk menekan kreativitas dan menyiapkan manusia hanya sebagai alat produksi. Pendidikan versi kolonial membuat rakyat kehilangan jati diri dan martabat.
3. Kembali ke Indonesia dan Lahirnya Taman Siswa
Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1922, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa bukan hanya lembaga pendidikan formal, melainkan gerakan sosial budaya yang menjunjung tinggi kemerdekaan dalam belajar dan pentingnya pendidikan berbasis kebudayaan nasional.
Taman Siswa membawa semangat anti-penindasan dan berupaya memberikan pendidikan kepada rakyat jelata, bukan hanya kalangan elit. Sistem pengajarannya menolak nilai-nilai kolonial seperti kekakuan, penghafalan, dan kekuasaan otoriter guru. Sebaliknya, pendidikan harus menyenangkan, mendidik akal dan hati, serta menjadikan murid sebagai manusia utuh.
4. Filosofi Pendidikan: Tut Wuri Handayani
Ki Hadjar Dewantara merumuskan tiga prinsip pendidikan yang terkenal hingga kini:
-
Ing Ngarso Sung Tulodo – di depan memberi teladan
-
Ing Madyo Mangun Karso – di tengah membangun semangat
-
Tut Wuri Handayani – di belakang memberi dorongan
Filosofi ini mengandung makna mendalam: guru dan pendidik tidak selalu harus menjadi pusat pengetahuan, tapi harus mampu menyesuaikan peran sesuai konteks — sebagai panutan, motivator, dan pendukung. Prinsip ini begitu kuat sehingga menjadi semboyan resmi Kementerian Pendidikan Indonesia.
5. Penolakan terhadap Pendidikan Elitis dan Komersial
Salah satu kontribusi revolusioner Ki Hadjar Dewantara adalah penolakannya terhadap pendidikan yang elitis dan dikomersialkan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah hak semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itu, Taman Siswa juga memberikan pendidikan gratis dan tidak membebankan biaya mahal kepada murid.
Lebih dari itu, ia mengkritik keras sistem ujian yang hanya mengukur intelektualitas sempit, tanpa memperhatikan budi pekerti, kreativitas, dan kemampuan sosial. Ki Hadjar menginginkan pendidikan yang menyeluruh dan holistik.
6. Kiprah sebagai Menteri dan Pengakuan Negara
Setelah Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia. Di sinilah ia merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional yang mencerminkan semangat kemandirian, kepribadian bangsa, dan pembentukan karakter.
Pada tahun 1959, pemerintah menetapkan tanggal lahirnya, 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal ini bukan semata penghargaan simbolik, tapi pengakuan atas jasanya dalam membentuk dasar pendidikan Indonesia yang merdeka dan berkarakter.
7. Relevansi Pemikiran di Era Modern
Meskipun telah wafat pada tahun 1959, pemikiran Ki Hadjar Dewantara tetap hidup dan relevan, khususnya dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini:
-
Pendidikan Merdeka: Di tengah dominasi teknologi dan sistem pendidikan seragam, gagasan tentang kemerdekaan belajar menjadi sangat penting agar siswa tidak kehilangan kreativitas dan identitas.
-
Kebudayaan sebagai Pondasi: Pendidikan tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Ini menjadi penting agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya di tengah arus globalisasi.
-
Guru sebagai Fasilitator: Era digital menuntut peran guru berubah dari pengajar menjadi pembimbing dan pendamping. Konsep Tut Wuri Handayani menjadi lebih bermakna di era pembelajaran mandiri.
-
Akses Pendidikan yang Merata: Dalam konteks ketimpangan ekonomi dan geografis, semangat Taman Siswa untuk menyediakan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat tetap menjadi inspirasi kebijakan pendidikan inklusif.
Kesimpulan
Ki Hadjar Dewantara bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi seorang pemikir besar yang membentuk fondasi pendidikan bangsa. Ia mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah yang membebaskan manusia dari kebodohan, ketergantungan, dan ketidakadilan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan beliau: menciptakan sistem pendidikan yang merdeka, kreatif, berakar pada budaya, dan mampu mencetak manusia berkarakter.
Dengan memahami gagasannya, kita tidak hanya menghormati sejarah, tetapi juga menyusun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan bermakna.











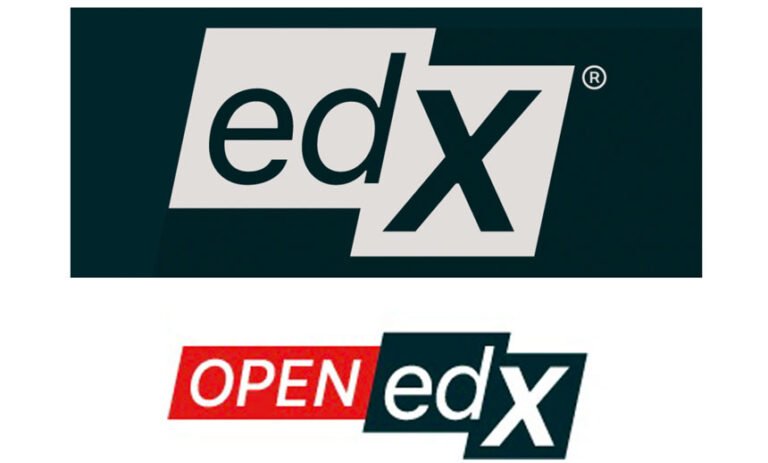




















Responses