CINULU.id – Implementasi Kurikulum Merdeka menandai sebuah era baru dalam lanskap pendidikan Indonesia, mengedepankan semangat otonomi, fleksibilitas, dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di tengah transformasi ini, para pendidik dihadapkan pada tugas krusial yang menjadi fondasi dari seluruh proses pembelajaran: menerjemahkan Capaian Pembelajaran (CP) menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang efektif. Proses ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan esensi dari peran guru sebagai perancang pengalaman belajar yang bermakna.
Kemampuan untuk membedah tujuan besar yang ditetapkan pemerintah (CP) menjadi langkah-langkah belajar yang logis dan terukur (ATP) adalah kompetensi kunci yang membedakan implementasi Kurikulum Merdeka yang sekadar berjalan dengan yang benar-benar berhasil memberdayakan peserta didik. Proses ini menuntut pemahaman mendalam terhadap filosofi kurikulum, keterampilan analisis, serta visi pedagogis yang jelas.
Artikel ini disajikan sebagai panduan lengkap Kurikulum Merdeka yang secara sistematis akan menguraikan setiap tahapan, dari pemahaman konseptual hingga aplikasi praktis di ruang kelas. Tujuannya adalah untuk membekali para pendidik dengan strategi dan perangkat yang dibutuhkan untuk merancang peta jalan pembelajaran yang tidak hanya koheren, tetapi juga mampu menginspirasi dan memfasilitasi kemajuan belajar setiap murid secara optimal.
Memahami Esensi Kurikulum Merdeka
Sebelum mendalami aspek teknis penyusunan perangkat ajar, pemahaman terhadap landasan filosofis Kurikulum Merdeka adalah sebuah prasyarat mutlak. Tanpa menginternalisasi “jiwa” dari kurikulum ini, proses turunan dari CP ke ATP berisiko menjadi mekanis dan kehilangan makna. Kurikulum Merdeka lahir sebagai respons strategis terhadap tantangan learning crisis yang telah lama menjadi perhatian, dan dampaknya semakin terasa akibat disrupsi pandemi COVID-19. Kurikulum ini dirancang secara fundamental untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam mengembangkan kurikulum operasional yang relevan dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan unik peserta didiknya.
Terdapat beberapa karakteristik utama yang menjadi pilar Kurikulum Merdeka dan wajib menjadi fondasi dalam setiap perencanaan pembelajaran:
- Fokus pada Materi Esensial: Salah satu perubahan paling signifikan adalah penyederhanaan konten. Kurikulum ini secara sadar mengurangi kepadatan materi agar pendidik dapat memusatkan perhatian pada konsep-konsep yang paling fundamental dan esensial. Tujuannya jelas: memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mendalami konsep secara mendalam (deep learning), menguatkan kompetensi, dan menjadikan proses belajar lebih bermakna, tidak terburu-buru, serta menyenangkan.
- Fleksibilitas dan Otonomi Pendidik: Kurikulum Merdeka mengembalikan otonomi profesional kepada guru. Ini adalah pergeseran paradigma dari yang sebelumnya sangat terstruktur menjadi lebih fleksibel. Pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi perangkat ajar, mengatur alokasi waktu pembelajaran (jam pelajaran diatur per tahun, bukan per minggu), dan yang terpenting, merancang pembelajaran terdiferensiasi yang sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik.
- Pengembangan Karakter dan Kompetensi Holistik: Visi jangka panjang dari Kurikulum Merdeka terangkum dalam Profil Pelajar Pancasila. Ini bukan sekadar tambahan, melainkan tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan. Enam dimensi—beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong-royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif—menjadi kompas yang mengarahkan setiap kegiatan pembelajaran, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Dengan memahami ketiga pilar ini, proses penyusunan CP ke ATP menjadi lebih dari sekadar tugas teknis. ATP yang dirancang harus menjadi manifestasi dari materi esensial, disusun dengan memanfaatkan fleksibilitas yang ada, dan senantiasa berorientasi pada pembentukan kompetensi serta karakter Profil Pelajar Pancasila.
Mendekonstruksi Capaian Pembelajaran (CP): Membedah Titik Awal dan Tujuan Akhir Pembelajaran
Capaian Pembelajaran (CP) merupakan kompetensi pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berfungsi sebagai acuan standar yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir setiap fase. Fase dalam Kurikulum Merdeka adalah pengelompokan jenjang pendidikan berdasarkan rentang waktu 1 hingga 3 tahun (misalnya, Fase A untuk Kelas 1-2 SD, Fase D untuk Kelas 7-9 SMP) untuk memberikan fleksibilitas dalam mencapai kompetensi.8 Dalam analogi sebuah perjalanan, CP adalah tujuan umum di akhir destinasi, sementara fase adalah alokasi waktu yang tersedia untuk menempuh perjalanan tersebut.
Untuk dapat menerjemahkan CP secara efektif, pendidik harus mampu “membaca” dan mendekonstruksi naskah CP mata pelajarannya. Struktur naskah CP umumnya terdiri dari empat komponen kunci :
- Rasional: Bagian ini menjelaskan justifikasi dan urgensi mempelajari mata pelajaran tersebut, serta keterkaitannya dengan pengembangan Profil Pelajar Pancasila.
- Tujuan: Menguraikan kemampuan atau kompetensi umum yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan seluruh fase pembelajaran pada mata pelajaran tersebut.
- Karakteristik: Mendeskripsikan elemen-elemen atau domain-domain inti yang menjadi ciri khas dan membentuk struktur keilmuan mata pelajaran.
- Capaian per Fase: Ini adalah bagian paling operasional yang menjadi fokus utama guru. Bagian ini ditulis dalam bentuk paragraf yang merangkaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai peserta didik di akhir fase tertentu.
Langkah fundamental yang harus dilakukan pendidik adalah menganalisis secara cermat paragraf Capaian per Fase yang relevan dengan jenjang yang diampu. Dalam proses analisis ini, identifikasi dan tandai kata-kata kunci yang merujuk pada dua hal: kompetensi (biasanya direpresentasikan oleh kata kerja yang menunjukkan kemampuan atau tindakan) dan lingkup materi (konten, konsep, atau topik utama yang harus dipelajari). Proses dekonstruksi inilah yang menjadi fondasi dan jembatan untuk merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP) yang lebih spesifik dan operasional.
Merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP): Menjabarkan Kompetensi dan Lingkup Materi Secara Terukur
Setelah CP berhasil didekonstruksi, langkah berikutnya adalah menerjemahkannya ke dalam unit-unit pembelajaran yang lebih kecil dan dapat dicapai, yang disebut Tujuan Pembelajaran (TP). TP merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang perlu dibangun oleh peserta didik melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. TP berfungsi sebagai “anak tangga” yang akan dipijak siswa untuk secara bertahap mencapai puncak, yaitu CP di akhir fase.
Berdasarkan panduan resmi dari Kemendikbudristek, sebuah TP yang efektif dan terukur harus memuat dua komponen utama:
- Kompetensi: Merujuk pada kemampuan atau keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Komponen ini harus dinyatakan dalam bentuk kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Pertanyaan panduan untuk menentukannya adalah: “Kemampuan konkret apa yang harus ditunjukkan siswa?” atau “Tahap berpikir apa yang diharapkan?”
- Lingkup Materi: Merujuk pada konten, konsep, atau topik utama yang perlu dipahami peserta didik pada akhir sebuah unit pembelajaran. Pertanyaan panduannya adalah: “Materi spesifik apa yang perlu dipelajari siswa dari konsep besar yang ada di CP?”
Untuk memastikan komponen kompetensi dirumuskan secara presisi, pendidik sangat dianjurkan untuk memanfaatkan kerangka kerja taksonomi kognitif yang telah teruji, seperti Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Kerangka ini menyediakan hierarki level kognitif, mulai dari
Mengingat (C1), Memahami (C2), Mengaplikasikan (C3), Menganalisis (C4), Mengevaluasi (C5), hingga Mencipta (C6). Pemilihan kata kerja operasional yang tepat dari taksonomi ini akan memastikan TP menjadi jelas, terukur, dan tidak ambigu.
Contoh Praktis Perumusan TP dari CP
Sebagai ilustrasi, mari kita ambil contoh dari CP IPAS Fase C (untuk Kelas 5-6):
CP: “Peserta didik menyelidiki bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, serta merancang solusi untuk menanggulanginya.”
Proses Dekonstruksi dan Perumusan TP:
- Analisis CP:
- Kompetensi (Kata Kerja): menyelidiki, mengidentifikasi, merancang solusi.
- Lingkup Materi (Konsep): perubahan kondisi alam (akibat faktor alam dan manusia), pola hidup penyebab pencemaran, solusi penanggulangan pencemaran.
- Rumusan TP yang Mungkin Dihasilkan:
- TP 1: Peserta didik mampu menjelaskan (C2 – Memahami) dengan kalimat sendiri contoh perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh faktor alam (misalnya, letusan gunung berapi, gempa bumi) dan faktor manusia (misalnya, penggundulan hutan, pembangunan).
- TP 2: Peserta didik mampu mengidentifikasi (C4 – Menganalisis) minimal tiga pola hidup dalam kehidupan sehari-hari yang berkontribusi terhadap pencemaran air di lingkungan sekitar mereka.
- TP 3: Peserta didik mampu merancang (C6 – Mencipta) sebuah poster kampanye sederhana yang berisi usulan solusi untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di lingkungan sekolah.
Dari contoh tersebut, terlihat jelas bagaimana setiap TP memiliki satu kata kerja operasional (kompetensi) yang spesifik dan lingkup materi yang terfokus. TP-TP inilah yang akan menjadi blok bangunan untuk menyusun ATP.
Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP): Merangkai Peta Jalan Belajar yang Logis dan Koheren
Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) adalah rangkaian Tujuan Pembelajaran (TP) yang disusun secara sistematis dan logis dalam satu fase. ATP berfungsi sebagai peta jalan atau skenario pembelajaran bagi guru dan peserta didik untuk memastikan CP dapat tercapai secara bertahap dan tuntas di akhir fase. Dalam praktiknya, ATP memiliki fungsi yang serupa dengan silabus pada kurikulum sebelumnya, yaitu sebagai kerangka perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen untuk jangka waktu satu tahun ajaran.
Pendidik memiliki fleksibilitas dalam pengadaan ATP: merancang sendiri dari awal, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, ataupun menggunakan contoh yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun, kemampuan untuk merancang ATP secara mandiri merupakan wujud nyata dari otonomi guru. Untuk menghasilkan ATP yang berkualitas, terdapat
tujuh prinsip utama yang perlu menjadi acuan:
- Sederhana dan Informatif: Menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.
- Esensial dan Kontekstual: Fokus pada kompetensi dan konten yang paling penting serta relevan dengan kehidupan nyata peserta didik.
- Berkesinambungan: Terdapat keterkaitan yang logis antar TP, membentuk sebuah alur yang runtut dan berjenjang.
- Pengoptimalan Tiga Aspek Kompetensi: Memastikan adanya keseimbangan dalam pengembangan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- Merdeka Belajar: Memberikan ruang untuk memfasilitasi keunikan setiap individu (kecepatan belajar, gaya, minat) dan mengoptimalkan peran guru sebagai perancang.
- Operasional dan Aplikatif: Rumusan ATP harus dapat diterjemahkan secara nyata ke dalam aktivitas pembelajaran dan asesmen di kelas.
- Adaptif dan Fleksibel: Dapat disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, kebutuhan peserta didik, dan kondisi unik satuan pendidikan.
Untuk mengurutkan TP menjadi sebuah alur yang logis, pendidik dapat menerapkan berbagai pendekatan strategis:
- Pengurutan dari Konkret ke Abstrak: Memulai dengan konsep yang dapat diamati secara langsung sebelum beralih ke teori atau simbol yang abstrak.
- Pengurutan Deduktif: Bergerak dari pemahaman konsep umum menuju analisis contoh-contoh yang lebih spesifik.
- Pengurutan dari Mudah ke Sulit: Mengajarkan keterampilan atau konten yang lebih sederhana sebagai fondasi sebelum memperkenalkan materi yang lebih kompleks.
- Pengurutan Hierarki: Memastikan kompetensi prasyarat diajarkan terlebih dahulu sebelum kompetensi yang lebih tinggi.
- Pengurutan Prosedural: Mengajarkan langkah-langkah suatu proses sesuai dengan urutan kronologisnya.
Proses penyusunan ATP ini idealnya dilakukan secara kolaboratif oleh para guru yang mengajar dalam satu fase yang sama (misalnya, guru Kelas 5 dan 6 untuk Fase C). Kolaborasi ini krusial untuk memastikan adanya kesinambungan pembelajaran dan menghindari tumpang tindih atau kesenjangan materi antar tingkatan kelas.
Implementasi, Tantangan, dan Solusi Praktis bagi Pendidik
ATP yang telah tersusun dengan baik bukanlah produk akhir, melainkan sebuah peta yang akan memandu langkah selanjutnya: perancangan Modul Ajar (sebagai pengganti RPP yang lebih lengkap dan fleksibel) serta strategi asesmen yang komprehensif (diagnostik, formatif, dan sumatif). Namun, proses implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus.
Berbagai studi dan laporan dari para praktisi mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh pendidik:
- Kesulitan dalam Pemahaman Konseptual: Istilah-istilah baru seperti CP, TP, ATP, dan struktur berbasis fase seringkali membutuhkan waktu untuk dipahami dan diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari.
- Peningkatan Beban Kerja: Terutama pada tahap awal implementasi, guru merasakan adanya peningkatan beban kerja terkait penyusunan perangkat ajar yang baru dari awal.
- Keterbatasan Pelatihan dan Referensi: Banyak pendidik merasa kurang mendapatkan pelatihan yang bersifat aplikatif dan kesulitan menemukan contoh-contoh konkret yang sesuai dengan konteks lokal sekolah mereka.
- Kompleksitas Pembelajaran Terdiferensiasi: Menganalisis kebutuhan belajar siswa yang sangat beragam dan merancang pengalaman belajar yang berbeda untuk setiap kelompok merupakan tantangan pedagogis yang signifikan.
Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang proaktif dan kolaboratif. Kunci utamanya adalah kolaborasi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- Mengoptimalkan Komunitas Belajar (Kombel): Jadikan Kombel, baik di tingkat sekolah maupun antar-sekolah, sebagai wadah utama untuk berdiskusi, membedah CP, dan menyusun ATP secara bersama-sama. Praktik berbagi ide dan beban kerja terbukti sangat efektif dalam meringankan tugas individu dan meningkatkan kualitas perangkat ajar yang dihasilkan.
- Kolaborasi Antar Guru dalam Satu Fase: Kerjasama antara guru yang mengajar di fase yang sama (misalnya, guru Kelas 1 dan 2) adalah sebuah keharusan. Kolaborasi ini memastikan bahwa ATP yang disusun benar-benar berkesinambungan dan setiap guru memahami apa yang telah dan akan dipelajari oleh peserta didik di seluruh rentang fase tersebut.
- Memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM): PMM merupakan sumber daya yang sangat kaya. Platform ini menyediakan ribuan contoh ATP, Modul Ajar, dan berbagai perangkat ajar lainnya yang dapat diunduh dan diadaptasi. Prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) sangat relevan di sini; pendidik tidak harus memulai dari nol.
- Mengikuti Pelatihan yang Efektif dan Relevan: Pilihlah program pengembangan profesional yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memberikan sesi praktik langsung, studi kasus, dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata para guru di lapangan.
Kesimpulan Panduan Lengkap Kurikulum Merdeka
Proses penerjemahan dari Capaian Pembelajaran (CP) ke Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) merupakan jantung dari perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Ini adalah proses intelektual dan profesional yang mengukuhkan peran guru sebagai perancang pengalaman belajar yang otonom dan kompeten. Meskipun menuntut pemahaman konseptual yang baru, keterampilan analisis yang tajam, dan komitmen untuk berkolaborasi, penguasaan proses ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari Kurikulum Merdeka.
Dengan mengikuti panduan ini—mulai dari menghayati esensi kurikulum, mendekonstruksi CP, merumuskan TP yang terukur, menyusun ATP yang logis, hingga secara proaktif mencari solusi atas berbagai tantangan—para pendidik di seluruh Indonesia akan mampu menciptakan alur pembelajaran yang tidak hanya selaras dengan kebijakan, tetapi yang terpenting, mampu menyalakan api keingintahuan, menumbuhkan kompetensi esensial, dan membentuk karakter mulia pada setiap peserta didik.
Referensi:
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) No. 033/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Longman.
- Fanggidae, F. S. T. (2023). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Guru Sekolah Dasar di Wilayah Pedesaan Pulau Sumba. HINEF: Jurnal Rumpun Ilmu Pendidikan, 2(2), 23–29.
- Pemahaman Dasar Konsep Kurikulum Merdeka | PDF – Scribd, diakses Agustus 12, 2025, https://id.scribd.com/document/680604847/Pemahaman-Dasar-Konsep-Kurikulum-Merdeka





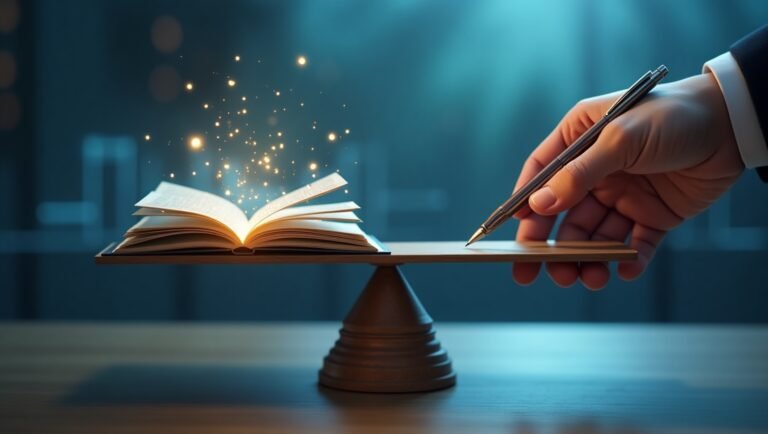

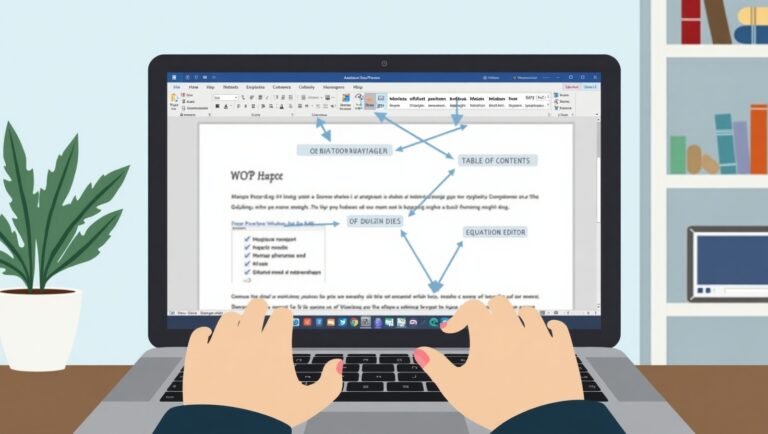



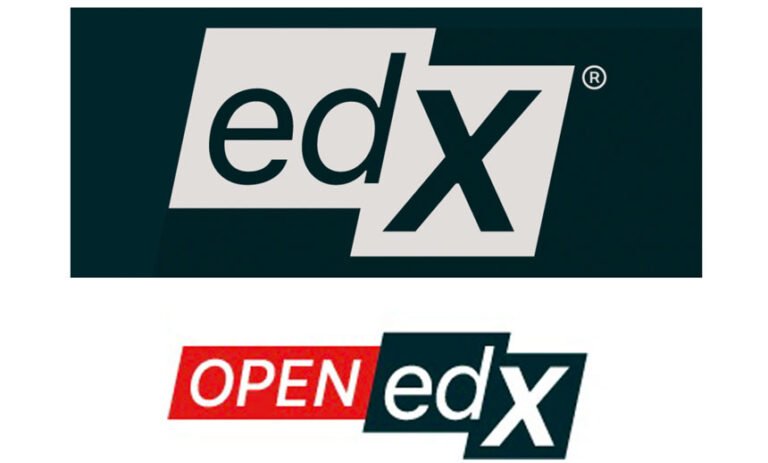




















Responses