Dalam sebuah diskusi tentang new earth conciousness muncul pertanyaan yang menggelitik : “Apakah manusia berada di dalam alam semesta, ataukah alam semesta berada di dalam diri manusia?” tidak hanya sekadar teka-teki retoris, melainkan benih yang menumbuhkan perenungan mendalam dalam sejarah filsafat, spiritualitas, hingga sains modern.
Ia menantang dikotomi antara luar dan dalam, antara subjektif dan objektif, antara pengalaman dan kenyataan. Dalam lanskap eksistensi ini, manusia tidak lagi sekadar makhluk kecil yang terlempar ke dunia, melainkan titik temu antara semesta yang kasat mata dan kesadaran yang tak terukur.
Secara ilmiah, kita sering diposisikan sebagai entitas kecil di tengah jagat raya yang sangat luas. Kosmologi modern menggambarkan manusia hidup di planet kecil bernama Bumi, yang mengorbit bintang biasa di pinggiran galaksi, yang juga hanyalah satu dari lebih dari dua triliun galaksi di alam semesta yang teramati (Mather, 2017).
Dari sudut pandang ini, jelas manusia “berada” di dalam alam semesta, layaknya sebutir debu dalam padang pasir. Namun, filsafat tidak pernah berhenti pada data. Ia mengejar makna. Dalam pandangan tradisi mistik Timur, seperti Vedanta dan Buddhisme Mahayana, manusia bukanlah sekadar penghuni alam, tetapi cerminan semesta itu sendiri.
Di dalam Chandogya Upanishad, misalnya, dikatakan: Tat Tvam Asi “Engkau adalah itu” yaitu bahwa hakikat individu adalah identik dengan hakikat semesta (Radhakrishnan, 1999). Dalam tradisi Sufi, Jalaluddin Rumi menulis: “Engkau bukan setetes air di lautan, engkau adalah lautan dalam setetes air.”
Gagasan bahwa alam semesta hadir dalam batin manusia juga mendapat dukungan dari filsafat modern, khususnya Immanuel Kant. Dalam Critique of Pure Reason, Kant menyatakan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas eksternal, melainkan bentuk-bentuk apriori dari intuisi manusia; artinya, kita tidak mengetahui dunia sebagaimana adanya (noumenon), melainkan sebagaimana ia tampak kepada kita (phenomenon) (Kant, 1781/2003).
Dengan kata lain, pengalaman akan semesta hanyalah mungkin dalam batas struktur kesadaran manusia. Konsepsi ini diperdalam oleh Edmund Husserl melalui pendekatan fenomenologisnya.
Husserl menegaskan bahwa segala bentuk makna, termasuk tentang “dunia” dan “realitas luar”, pertama-tama dan terutama adalah konstitusi dalam kesadaran (Husserl, 1931). Tanpa kesadaran, tidak ada dunia yang dapat dikatakan “ada” dalam pengertian pengalaman. Maka, bisa dikatakan, alam semesta sebagaimana kita pahami hanya eksis sejauh ia dipahami.
Pandangan ini bukan sekadar idealisme abstrak. Sains kontemporer pun mulai menyentuh wilayah yang selama ini diasosiasikan dengan metafisika. Dalam fisika kuantum, eksperimen celah ganda (double-slit experiment) menunjukkan bahwa partikel (seperti elektron) berperilaku berbeda tergantung apakah diamati atau tidak.
Ketika tidak diamati, partikel berperilaku seperti gelombang yang menyebar, namun ketika diamati, ia bersikap seperti partikel yang pasti posisinya (Rosenblum & Kuttner, 2011). Fenomena ini membuka celah bahwa kesadaran pengamat memainkan peran dalam realitas fisik.
Fisikawan modern seperti Carlo Rovelli bahkan menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta bersifat relasional tidak ada objek yang eksis secara mutlak, melainkan hanya dalam relasinya dengan yang lain (Rovelli, 2017).
Dengan demikian, subjek dan objek bukan dua entitas yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu mata uang realitas. Alam semesta tidak “di luar sana”, melainkan juga “terjadi” dalam hubungan dengan kesadaran manusia.
Kita juga bisa melihat tubuh manusia sebagai miniatur dari semesta itu sendiri. Dalam konsep mikrokosmos–makrokosmos yang banyak berkembang sejak zaman Hermetisme, tubuh manusia memuat prinsip-prinsip yang serupa dengan struktur kosmos.
Dari sistem peredaran darah yang menyerupai sungai-sungai, hingga jaringan saraf yang mencerminkan konstelasi galaksi, kita menyaksikan bahwa “yang besar tercermin dalam yang kecil” (Capra, 1996).
Sains molekuler menguatkan hal ini. DNA manusia, misalnya, menyimpan informasi genetik dalam bentuk yang sangat padat, sekitar tiga miliar pasangan basa nitrogen, membentuk sistem kompleks yang dapat dikatakan lebih rumit daripada sistem komputasi mana pun yang pernah dibuat.
Jika dibentangkan, total panjang DNA dalam satu sel manusia bisa mencapai dua meter, dan jika seluruh DNA dari tubuh kita disambung, panjangnya bisa menembus jarak ke matahari ribuan kali (National Human Genome Research Institute, 2020). Kita bukan sekadar bagian kecil dari semesta, kita adalah semesta yang terlipat dalam bentuk biologis.
Semua pengalaman tentang dunia ini terjadi di dalam kesadaran. Ketika kita bermimpi, kita bisa mengalami semesta penuh yang tampak nyata, lengkap dengan ruang, waktu, bahkan emosi. Namun, saat kita terbangun, kita menyadari bahwa semuanya terjadi di dalam pikiran.
Ini mengangkat pertanyaan: apakah dunia yang sekarang ini kita alami juga semacam mimpi hanya saja dalam skala kesadaran yang lebih kolektif dan konsisten? Filsuf India, Shankara, menyebut dunia ini sebagai Maya tirai ilusi yang menyelubungi realitas sejati (Deutsch, 1980).
George Berkeley, filsuf idealis dari abad ke-18, menegaskan: Esse est percipi” menjadi adalah untuk dipersepsi”. Bagi Berkeley, benda tidak eksis kecuali dalam persepsi; dunia adalah konstruksi persepsi dalam kesadaran ilahi maupun manusia (Berkeley, 1710).
Ini bukan berarti dunia adalah delusi, tetapi bahwa eksistensinya tak bisa dipisahkan dari kesadaran yang menyadari. Dengan cara pandang ini, semesta bukanlah wadah pasif tempat manusia hidup, tetapi keberadaan yang muncul dalam tarian kesadaran.
Apa makna dari semua ini? Jika semesta berada di dalam manusia atau lebih tepatnya, dalam kesadaran manusia, maka konsekuensinya bersifat etis dan spiritual. Kita tak bisa lagi memandang realitas sebagai “yang lain”, sebagai objek yang boleh kita eksploitasi sesuka hati.
Sebaliknya, segala sesuatu yang kita temui, baik manusia, binatang, air, batu, bintang adalah bagian dari kesadaran yang sama, bagian dari diri kita sendiri dalam bentuk lain. Dalam spiritualitas Yesus seperti tertulis dalam Injil Thomas, ada kutipan menarik: “Kerajaan Allah tidak datang dengan pengamatan… Kerajaan itu ada di dalam dirimu dan di sekitarmu” (Meyer, 2005).
Artinya, realitas spiritual tertinggi tidak dicapai dengan mencari keluar, tetapi dengan menyelam ke dalam. Hal serupa disampaikan oleh Buddha Gautama: “Dengan mengenal diri sendiri, dunia dikenali.”
Pandangan ini bukan pengasingan dari dunia, tapi integrasi dengan dunia. Kita tidak lagi melihat diri sebagai makhluk terlempar ke semesta yang asing, melainkan sebagai ekspresi dari semesta itu sendiri. Kita tidak hanya “berada” di dalam alam semesta, kita adalah alam semesta yang menyadari dirinya—kesadaran yang dapat bertanya, merenung, mencipta, dan mencinta.
Barangkali inilah yang dimaksud oleh Carl Sagan ketika ia berkata, “We are a way for the cosmos to know itself.” Kita bukan makhluk terisolasi, tapi refleksi dari jagat raya dalam bentuk manusia. Semesta tidak hanya di luar sana; ia hidup, bernapas, dan berpikir dalam diri kita.
Maka, di mana kita berada? Mungkin jawaban terbaik bukan memilih satu sisi, bukan di luar atau di dalam, melainkan menyadari bahwa batas itu sendiri ilusi. Kita adalah persinggungan antara kedalaman batin dan luasnya ruang angkasa. Kita adalah titik temu antara langit dan bumi, antara yang fana dan yang kekal. Alam semesta tidak hanya mengelilingi kita. Ia juga bergetar dalam hati kita.











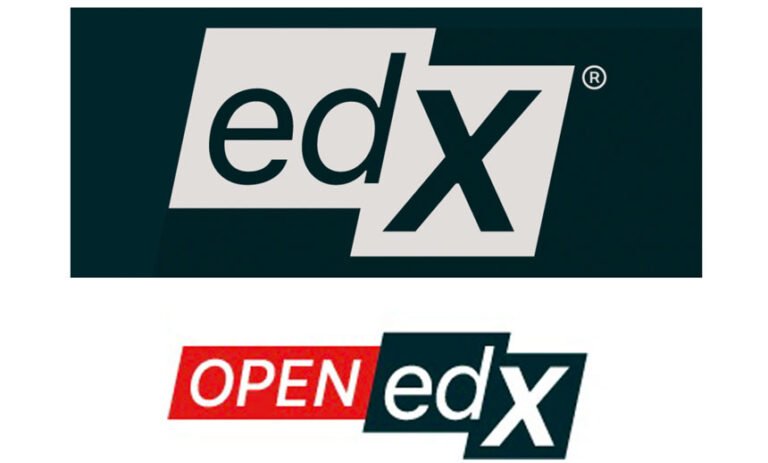




















Responses